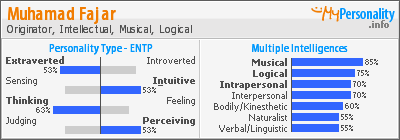2 Oktober 2013
Lebih 68 tahun silam negara kita merdeka. Mendeklarasikan diri sebagai bangsa Indonesia, bukan Hindia Belanda. Membebaskan diri dari palung label kebodohan ciptaan bangsa Imperialis. Iya kita bebas sebagai makhluk. Bukan lagi budak dari makhluk lain.
Hmm.. tapi kenapa? Hari ini masih kulihat kehidupan di pojok pulau Nusantara, anak-anak berlari tanpa sandal, baju, atau bahkan celana. Hidup seperti anak ayam yang dilepas mencari makan oleh induknya. Atau orang-orang yang hanya sempat makan satu kali sehari ... eh hanya bisa makan satu kali sehari, karena dirundung oleh budaya kemiskinan, gempuran budaya konsumerisme, plus kerusakan moral. Semua karena tidak ada yang menekan mereka agar sekolah, atau tak ada yang menoleh ke arah mereka. Siapa mereka? Apa peduliku? Mereka tidak sekolah? Salah mereka sendiri! Begitukan pikirmu para Insinyur?
Aku tidak sedang mengutuk kemiskinan yang mendera sebagian bangsa Indonesia. Tidak pula mengutuk para pemikir cerdas namun culas yang sedang mengaku sebagai representasi rakyat. Hanya saja aku ingin bertanya kepada para insinyur yang asal usul katanya engineer dan bermakna perekayasa. Wahai para insinyur abad 21, tidakkah seharusnya kecerdasan dan ilmu yang kita miliki bisa menjadi kekuatan untuk menciptakan kesejahteraan atau bahasa kerennya kemakmuran bagi keluarga serumpun dan sebangsa kita? Atau hidup yang sekali ini sebaiknya cukup kita nikmati dan eksploitasi untuk kesenangan diri, kesenangan keluarga, dan kesenangan - kesenangan lainnya yang bersifat privat, terbatas, lagi eksklusif? Sungguh dunia yang sebentar ini berhasil menipu kita!
Insinyur Soekarno, berpendidikan, muda, gagah, dan cerdas. Di umur 24 tahun membuat propaganda melalui berbagai media untuk meyakinkan manusia Nusantara bahwa mereka sudah cukup cerdas dan hebat untuk lepas dari perbudakan bangsa lain. Berbekal ilmu dan wawasan yang diperolehnya dari jenjang pendidikan dasar sampai tinggi membuatnya cukup kritis dan berani menantang arus besar sang penguasa semu Nusantara. Mungkin terinspirasi dari cita-cita Patih Gajah Mada, cita - cita sederhana, menyatukan manusia Nusantara untuk kepentingan kemakmuran bangsa dan dunia. Ya... dia membuang kesempatan untuk menjadi Ambtenar budak elit bangsa barat. Harus meniti jalanan melelahkan lagi menyiksa. Harus berhadapan dengan kawan-kawannya sendiri yang beda pendapat. Hmm ... tapi lihat hari ini?
HOS Cokro Aminoto, bangsawan, terdidik, tetapi berhati mulia. Mentor Ir. Soekarno semasa mahasiswa. Tidak rela lihat rakyat non bangsawan hidup susah. Susah makan, susah minum, susah senang, susah sedih, susah hidup, dan susah mati. Beliau memilih memanggul karung ke pasar asal bisa makan dan bergemelut mempersatukan manusia cerdas dalam panji Tuhan Semesta Alam. Membuang pula takdir darah biru yang serba terjamin enak dari hidupnya, demi kebebasan bangsanya. Hmm... Berapa banyak kemudian orang yang terilhami lagi terinspirasi dengan langkahnya?
Oh iya, kita kembali kepada diri kita para Insinyur abad 21. Tidakkah hidup kita juga hanya sekali? Jika mati selesai semua, maka apa hal yang mau kita goreskan dalam buku kehidupan kita? Membantu bangsa luar mengeksploitasi sumber daya alam negeri sendiri? Menerima pelicin untuk memperlancar urusan manusia menipu dan merampok manusia - manusia lainnya? Aih ... sungguh uang itu cuma kertas berdigit yang bisa dimain-mainkan bank dunia. Kalau benda itu bisa mengantarkan kita ke surga, kenapa mau kita buat benda itu jadi tiket ekspres ke neraka? Atau mungkin para insinyur lupa bahwa nyawanya cuma satu? Hidupnya cuma sekali? Apapun pilihanmu nyur, selamat menjalani hidupmu dan mengukir kisahmu. Semoga Dia menggolongkan kita sebagai orang-orang yang beruntung, ketika masih hidup dan juga ketika sudah mati.